Studi tentang teologi Ekaristi ini memuat sebuah uraian sistematik dari sudut pandang teologis, historis dan reflektif. Dalam konteks Teologi Dogmatik, teologi Ekaristi berkaitan erat dengan tema-tema dogmatik lainnya, seperti Trinitas, Kristologi, Eklesiologi, dan Eskatologi.
Pokok-pokok Pembahasan. Setelah pengantar, dipaparkan prinsip-prinsip umum Sakramen Ekaristi, termasuk istilah lain yang memperkaya makna istilah Ekaristi. Dalam studi ini Ekaristi direfleksikan sebagai sakramen persekutuan (communio) semesta, jadi tidak eksklusif sebagai sakramen Gereja. Sebagai sebuah tema teologis, Ekaristi ditempatkan sejarah keselamatan yang terungkap sejak Perjanjian Lama sampai peristiwa Yesus Kristus. Dimensi tersebut akan dipaparkan lebih jauh pada bab kedua, dengan berpijak pada akar biblis. Perlu digali beberapa narasi biblis yang memuat tipologi kontinuitas maupun diskontinuitas antara Paskah Yahudi, Perjamuan Akhir Yesus dan para murid-Nya, dan perayaan Ekaristi Gereja.
Penelusuran corak biblis Perjanjian Baru Sakramen Ekaristi akan dipaparkan pada bab ketiga. Para penulis Injil menarasikan Perjamuan Akhir sesuai konteks jemaat dan interese teologisnya. Meski demikian tujuan mereka sama: memaknai pemberian diri Yesus dan amanat Ekaristi yang keluar dari mulut-Nya. Empat teks dasar biblis Kisah Institusi (Paulus dan Sinoptik) adalah dasar tak tergantikan bagi teologi Ekaristi. Dalam Injil Yohanes tidak ditemukan sebuah Kisah Institusi. Meski demikian kisah pembasuhan kaki (Yoh. 13: 1-15) menekankan penyerahan diri Kristus bagi para murid. Tema Ekaristi yang mencolok dalam Injil Yohanes ialah ajaran tentang roti hidup (Yoh. 6), di mana Yesus mengungkapkan diri sebagai Roti Hidup, jaminan hidup kekal bagi para pengikut-Nya. Teks-teks lain tentang perjamuan makan selama hidup maupun sesudah kebangkitan Yesus tentu juga menjadi dasar biblis teologi Ekaristi.
Studi ini akan dilanjutkan dengan mengulas sebuah tahap penting dalam teologi Ekaristi, yaitu pandangan para Bapa Gereja, mulai dari para Bapa Gereja yang paling kuno, dilanjutkan dengan Gereja Timur dan Barat. Bagian ini penting karena memaparkan tipologi penafsiran atas ritus dan simbol Ekaristi. Tahap ini masih diwarnai narasi biblis maupun tradisi extra bilis (Didache), yang turut memberi landasan bagi refleksi teologis pada tahap-tahap selanjutnya.
Periode berikut yang tidak kurang kekayaannya ialah Abad Pertengahan. Konteks dan kekhasan pandangan beberapa tokoh mazhab ini akan dipaparkan. Pandangan para Skolastik kemudian mendorong tanggapan dari pihak Gereja Reformasi terhadap beberapa topik misalnya kuasa imam dalam merayakan Ekaristi, doktrin transsubstantiatio, penerimaan komuni dua rupa bagi umat dan pemaknaan Ekaristi sebagai kurban. Diskusi-diskusi tersebut mendorong Konsili Trente mengemukakan ajaran-ajarannya sebagai representasi sikap resemi Gereja Roma.
Setelah memberi sebuah perspektif atas tema-tema utama pandangan Konsili Trente, studi ini diperkaya dengan pandangan beberapa teolog modern dan kontemporer. Doktrin dari Konsili Trente seperti transsubstantatio dan kurban Ekaristi ditanggapi tokoh-tokoh modern. Bagian akhir studi ini memuat sebuah refleksi berdasarkan kesadaran ini: Interkoneksitas dunia berkat kemajuan sarana digital di satu pihak dan fakta individualisme dan krisis ekologi di pihak lain, menantang Gereja untuk kembali kepada communio Ekaristi, yaitu gairah yang memancarkan kecintaan bagi segenap ciptaan. Sebab itu, dimensi trinitaris, eklesial, sosio-ekonomi, ekologi, spiritualitas serta eskatologi dalam Ekaristi hendak direfleksikan secara integral.
Perspektif Communio. Istilah persekutuan pada kalimat judul studi ini dipilih sebagai paradigma dasar pemahaman dan refleksi teologis sakramen Ekaristi. Oleh sebab itu pemahaman dan makna istilah yang tersebut perlu dikemukakan terlebihdahulu. Sebagaimana diuraikan Gisbert Greshake (“Trinity as ‘Communio”, 331-345), makna kata communio (bahasa Latin) lebih dalam daripada bentukan etimologis cum + unio yang pada umumnya dimengerti sebagai ‘kesatuan antara satu dan yang lain’ (union with one onther). Dari segi lungistik, ada dua konotasi penting dari istilah yang dimaksud. Pertama, akar kata mun yang berarti kubu/benteng/tanggul (dalam bahasa Latin, kata moenia berarti tembok kota). Orang-orang yang berada dalam persekutuan (in communione) berada bersama dalam tembok atau benteng; satu orang bersatu dengan orang-orang lain atas dasar sebuah realitas yang komunal. Dalam kubu tersebut satu orang merupakan bagian dari semua orang.
Kedua, akar kata mun juga ekuivalen dengan kata munus dalam bahasa Latin yang berarti: tugas/pelayanan/persembahan, atau juga berarti rahmat/pemberian/hadiah. Orang-orang yang hidup dalam persekutuan disatukan oleh partisipasi pelayanan setiap pribadi demi satu tujuan bersama. Setiap anggota memainkan peran khusus, namun tidak bertentangan karena disatukan oleh satu keyakinan bersama. Oleh karena itu dikatakan bahwa satu orang hadir sebagai hadiah bagi orang lain, dan ia juga menerima pelayanan orang lain; dengan demikian mereka saling memberi dan menerima karena dipersatukan oleh sebuah keyakinan lebih luhur yang universal.
Setiap orang dalam kubu memang beragam. Namun keberagaman itu dipersembahkan bagi yang lain sehingga terjalin (menjadi mediasi) persekutuan universal. Dalam pemahaman ini, Greshake melihat bahwa makna communio cocok dengan makna kata koinōnia dalam bahasa Yunani. Kata koinōnia menunjuk communio serta perwujudannya, yaitu komunikasi (communicatio) – bukan hanya dalam arti memberi informasi tetapi hadir bagi yang lain.
Greshake berpandangan bahwa persekutuan Allah Tritunggal merupakan model bagi persekutuan-persekutuan yang diupayakan manusia. Sebagaimana akan diuraikan pada pokok lain, akar dari persekutuan Ekaristi adalah persekutuan Tiga Pribadi Ilahi. Persekutuan jemaat dalam Ekaristi Gereja dibangun di atas koinōnia. Sebagaimana akan ditunjukkan dalam pandangan Rasul Paulus (bdk 1Kor 10:16), persekutuan jemaat dalam Ekaristi dijiwai oleh koinōnia atau persekutuan setiap anggota jemaat dengan Kristus.
Dalam Ekaristi jemaat mengambil bagian dalam Kristus. Dalam persekutuan dengan Kristus, Ekaristi menjadi tidak terbatas pada dimensi eklesial, tetapi meluas, merangkul persekutuan segenap ciptaan. Ekaristi merangkul dunia sebagi altarnya. Dimensi ini terungkap dengan jelas dalam Ensiklik Laudato Sí Paus Fransiskus pada tema kasih kosmik: “Ekaristi menyatukan langit dan bumi, merangkul dan meresapi seluruh ciptaan. Dunia yang berasal dari tangan Allah, berbalik kepadanya dalam penyembahan yang penuh sukacita dan sempurna. … Oleh karena itu, Ekaristi adalah sumber terang dan motivasi untuk kepedulian kita akan lingkungan hidup, dan mengajak kita untuk menjadi penjaga seluruh ciptaan” (LS 236).
Teolog kontemporer Kenon Osborne OFM, dalam Komunitas, Ekaristi dan Spiritualitas (hlm, 12-122, 190-195) mengedepankan sebuah spiritualitas ekaristis yang membumi. Ia mengggarisbawahi hubungan erat antara Ekaristi dunia dan Ekaristi altar. Dalam Ekaristi orang menyantap hasil bumi dan karya manusia. Dengan latar belakang teologi Santo Bonaventura yang memaknai semesta sebagai buku ciptaan, ia merefleksikan bahwa spiritualitas Ekaristi hendaknya mengalir dalam tindakan membaca dan merenungkan kitab yang setiap hari dibuka oleh Allah Pencipta di hadapan kita. Sebagaimana Ekaristi adalah kehadiran sakramental Allah, demikian pula seluruh ciptaan itu sakral karena mengungkapkan karya seni sang Pelukis Agung. Seruan Ite missa est di akhir perayaan Ekaristi mengandung perutusan bagi komunitas ekaristis untuk siap membawa amanat Ekaristi ke dalam Ekaristi dunia.
Pemaknaan Ekaristi dengan persepektif communio dikembangkan juga oleh teolog kontemporer misalnya John Zizioulas (Communion & Otherness dan The Eucharistic Communion and the). Menurut Zizioulas: “Bukan kebetulan bahwa nama lain dari Ekaristi ialah communio. Sebab dalam Ekaristi kita menemukan semua dimensi persekutuan: Tuhan mengkominikasikan diri-Nya bagi kita, kita masuk dalam persekutuan dengan-Nya, semua yang mengambil bagian dalam Ekaristi membangun persekutuan satu bagi yang lain dan bersama segenap ciptaan, melalui manusia, menjalin sebuah persekutuan dengan Allah”.
Beberapa teolog Asia juga menekankan pentingnya sense of community (Amalados, “The Eucharist and the Christian Community”, 216-229) dalam komunitas ekaristis. Corak dasar komunitas ekaristis ialah sharing dan communion. Persekutuan ekaristis terdiri dari orang-orang yang berbagi kebaikan satu sama lain. Wujud konkret sense of community ialah solidaritas. Tanpa tindakan solidaritas, perayaan Ekaristi tidak sungguh bermakna. Wujud dari semangat Ekaristi ialah berbagi – juga dari kekurangan yang dimiliki. Teks Yoh 6: 1-15 menampilkan seorang anak yang memberi dari semua yang ia miliki tanpa membuat perhitungan: lima roti jelai dan dua ikan (ay 9). Yesus menghargai pemberian tulus itu, mengucap syukur atasnya dan membagi-bagikannya sehingga cukup untuk dimakan lima ribu orang. Kebaikan dari usaha manusia, meskipun tampak kecil, ketika diwujudkan dengan sungguh, dengan berkat dari Allah, akan mendatangkan solidaritas yang lebih besar dan luas.
Tantangan Berteologi. Corak persekutuan sebagaimana dijabarkan baru saja tentu berbeda dari ciri interkoneksitas dunia virtual yang maju begitu pesat sekarang, yang pantas disebut juga sebagai sebuah bentuk persekutuan. Pendekatan dalam studi ini masih menganut keyakinan bahwa dimensi menubuh dalam perayaan Ekaristi dan pemaknaan simbol-simbol sakramental dalam wujud elemen-elemen konkret (roti dan anggur) merupakan faktor yang tidak (belum?) tergantikan.
Dalam hal ini kami setuju misalnya dengan pandangan Antonio Spadaro (Cybertheology, 73-76, 88-01) bahwa dalam persekutuan sakramental seperti Ekaristi, terjalin komunikasi dan interaksi antara pribadi hic et nunc, bukan sekedar ketersambungan melalui jaringan media sosial, semacam Cyber-Eucharist yang bergantung pada jaringan internet. Berdasarkan keyakinan bahwa Gereja tidak identik dengan jaringan sosial (ultimate social network) mau ditegaskan bahwa persekutuan Ekaristi melibatkan seluruh dimensi diri manusia (spiritual sense, akal budi, kehendak bebas). Oleh karena itu kami sepekat dengan penegasan Antonio Spadaro: “there are no sacraments on the internet”.
Di lain pihak tidak dapat disangkal bahwa pada era kemajuan teknologi digital ini teologi dan spiritualitas Kristen sungguh ditantang. Pemaknaan Ekaristi sebagai perayaan persekutuan pun ditantang: Apakah pada suatu saat kehadiran menubuh dalam perayaan sakramental menjadi relatif, bahkan dapat digantikan dengan kehadiran virtual lantaran kemajuan intekoneksitas dunia digital? Diperlukan sebuah kajian khusus untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Dalam studi ini kami belajar dari karya-karya yang telah tersedia dalam bahasa Indonesia: Beberapa buku dan artikel kami muat dalam daftar bibliografi. Tidak semua menjadi acuan studi, namun tetap dicatat sebagai informasi atau acuan riset baru. Secara khusus kami banyak belajar dari pakar Ekaristi di Indonesia, Romo Emanuel Martasudjita. Beberapa ulasan dan terjemahan beliau, misalnya tentang pandangan Konsili Trente, sangat membantu kami. Studi kami juga berjalan berkat sarana dan iklim belajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Terima kasih khususnya bagi mahasiswa kelas Ekaristi dan teman-teman di perpustakaan yang selalu memberikan pelayanan terbaik. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada para saudara Fransiskan di persaudaraan “Duns Scotus” Kampung Ambon, atas gairah communio yang terus dibangun dalam wujud studi, doa dan karya pelayanan.
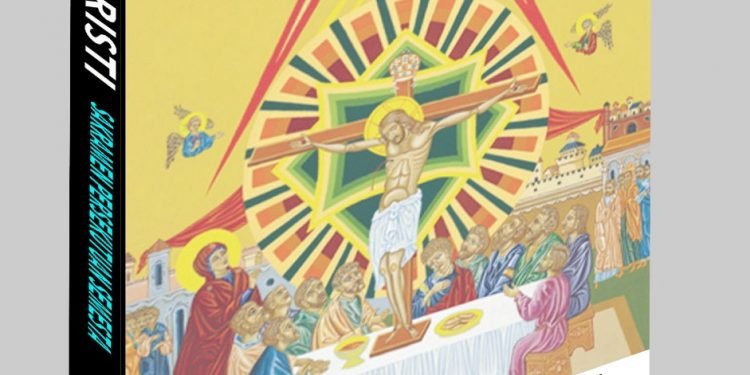
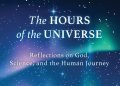

Wahh jd tau lbh jauh ttg Ekaristi.
Tks Pater Andre.
Salam sehat.Pace e bene